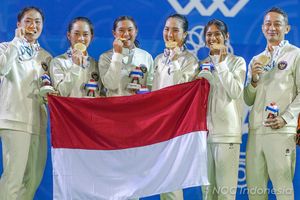Dayeuhkolot yang Tak Pernah Kering: Warga Bertahan dalam Derita Banjir Tanpa Akhir

"Kalau saya tetap memilih buka warung, ya meskipun air tinggi sampai 90 sentimeter juga tetap harus cari rezeki," katanya.
Sementara di sudut kampung, beberapa warga berdiri di teras rumah.
Anak-anak duduk berbaris bermain perahu, bak penumpang kapal yang menunggu nakhoda membawa mereka ke tanah yang lebih bersahabat.
Di sana, aroma Sungai Citarum yang mengendap sejak malam bercampur dengan bau solar dari sepeda motor yang mogok.
Semuanya bertaut menjadi satu: aroma kelelahan, aroma perjuangan, aroma hidup yang dipaksa terus berjalan.
Di balik deru air yang melintas pelan, ada cerita yang tidak pernah tersampaikan: tentang sandal-sandal yang hanyut malam tadi, tentang kasur yang tak lagi bisa mengering, tentang buku sekolah yang rusak sebelum sempat dibaca.
"Kondisi ini sudah lama, mungkin banyak faktor, daerah resapan yang sudah hilang, hasilnya ya Kampung kami ini terdampak," bebernya.
Namun, warga Kampung Leuwi Bandung tidak pernah benar-benar diam.
Mereka mengikat barang-barang, mengangkat lemari, menumpuk piring dan pakaian di rak paling tinggi, seakan membangun benteng kecil dari sisa-sisa harapan.
Perjuangan Bertahan
Tak hanya Robert, di rumah panggung sederhana, seorang nenek bernama Onih bertahan dengan kompor kecil yang dinaikkan di atas dua bata.
"Banjir ini seperti tamu lama, dia sudah tahu letak pintu, tahu letak dapur, bahkan tahu tempat tidur kita," katanya.
Setiap kali air naik setinggi lutut, warga tahu apa yang harus dilakukan.
Tak ada teriakan panik, yang ada hanya gerakan-gerakan yang telah menjadi ritus tahunan: mengemasi, mengangkat, memindah, mengevakuasi.
Meski demikian, di balik keterbiasaan itu, rasa letih mulai menggerus.
Banjir yang datang silih berganti membuat dinding semangat perlahan retak.